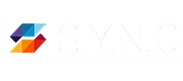SETIAP PEMBUNUH, siapa pun dia, tak peduli lelaki atau perempuan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Namun kenyataan, dalam sekian banyak persidangan, terdakwa perempuan menggunakan 'battered woman/wife syndrome' sebagai pembelaan diri. Para terdakwa itu menyebut telah mengalami penghinaan, penistaan, dan penganiayaan yang sedemikian buruknya dari pasangan, sampai-sampai tidak mampu lagi untuk berpikir secara rasional.
Dalam kondisi sedemikian terpuruk, tiada lain yang terpikir oleh para perempuan tersebut untuk membela diri dan keluar dari situasi pedih itu kecuali dengan menghabisi pasangannya.
Hakim bisa menjatuhkan vonis tak bersalah atau meringankan hukuman atas diri terdakwa jika teryakinkan bahwa terdakwa betul-betul menderita battered woman/wife syndrome. Itu terdakwa perempuan!
Bagaimana jika yang teraniaya sedemikian rupa adalah laki-laki atau suaminya? Saya kerap risau kalau dikatakan bahwa laki-laki adalah mayoritas pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Boleh jadi banyak laki-laki/suami yang menjadi korban KDRT, tapi mereka tidak melapor karena dianggap aib. Melapor malah membuka risiko mengalami secondary victimization, di-bully oleh penegak hukum maupun lembaga advokasi.
Anggaplah lelaki melakukan kekerasan fisik. Tapi seberapa besar kemungkinan lelaki bangun tidur sekonyong-konyong langsung menempeleng istri, kecuali jika si suami mabuk atau gila. Sayangnya, kita acap tidak cukup jauh berpikir bahwa kekerasan fisik lelaki bisa dilatarbelakangi oleh kekerasan verbal yang dilakukan perempuan.
Nah, jadi bisakah terdakwa lelaki yang menghabisi pasangannya menggunakan 'battered man/husband syndrome' sebagai pembelaan diri di persidangan?
Semestinya bisa saja. Toh hukum tidak diskriminatif. Toh para lelaki juga bisa terzalimi. Tapi siapakah kaum Adam yang bernyali membela diri dengan klaim tersebut?
(Reza Indragiri)